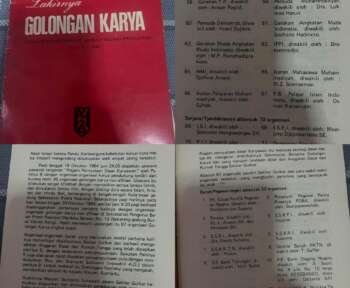Arief Rosyid Hasan (Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran / Ketum PB HMI 2013-2015)
Tulisan ini saya hadirkan sebagai respon atas artikel Bagas Kurniawan, Ketua Umum PB HMI, berjudul “Reformasi 2025: Jihad Institusi untuk Indonesia” di harian Kompas (11/9). Gagasannya penting, tetapi saya percaya bangsa ini membutuhkan narasi lebih visioner: transformasi Indonesia.
Reformasi 1998 membuka ruang demokrasi, membongkar otoritarianisme, dan memberi rakyat hak memilih langsung. Namun, setelah dua dekade, demokrasi prosedural tidak otomatis melahirkan keadilan atau kemajuan. Demokrasi bisa macet bila institusi rapuh dan meritokrasi terkikis.
Bonus Demografi
Bonus demografi menjadi modal terbesar Indonesia. Lebih dari 60 persen penduduk saat ini berada pada usia produktif. Momentum ini hanya datang sekali seabad. Salah kelola menjadi bencana. Dikelola dengan benar, ia menjadi mesin sejarah.
Generasi muda adalah inti bonus demografi. Mereka kreatif, digital native, dan berani mengambil risiko. Tetapi tanpa sistem yang adil, energi ini bisa hilang percuma. Negara wajib menjadikan mereka subjek pembangunan, bukan sekadar objek mobilisasi.
Fenomena global menunjukkan pelajaran penting. Jepang dan Korea Selatan berhasil melesat karena memanfaatkan bonus demografi. Sebaliknya, banyak negara Afrika gagal mengelola momentum ini, sehingga justru menghadapi pengangguran massal dan instabilitas sosial berkepanjangan.
Indonesia hari ini berada di persimpangan jalan sejarah. Apakah bonus demografi akan menjadi berkah atau justru musibah, sangat bergantung pada keberanian kita menegakkan meritokrasi dan memberi ruang luas bagi generasi muda.
Meritokrasi sebagai Jalan
Meritokrasi berarti kesempatan dibuka berdasarkan kapasitas, integritas, dan prestasi, bukan kedekatan. Tanpa meritokrasi, bonus demografi hanya menjadi beban. Dengan meritokrasi, energi muda dapat diubah menjadi inovasi, produktivitas, dan kepemimpinan baru.
Michael Young dalam The Rise of the Meritocracy (1958) pertama kali memperkenalkan istilah meritokrasi. Ia menegaskan sistem ini bisa adil bila berbasis prestasi, tetapi berbahaya jika dikendalikan segelintir elite yang menutup akses partisipasi.
Daniel A. Bell dalam The China Model (2015) menunjukkan bagaimana seleksi kepemimpinan berbasis merit mampu menjaga kesinambungan politik di Asia Timur. Sistem semacam ini membuktikan bahwa meritokrasi bukan hanya wacana, melainkan praktik nyata.
Indonesia juga bisa belajar dari Acemoglu dan Robinson dalam Why Nations Fail (2012). Mereka menekankan institusi inklusif dan meritokratis sebagai prasyarat inovasi. Sebaliknya, institusi ekstraktif hanya melahirkan stagnasi dan menutup peluang talenta.
Kita sempat melihat kilasan meritokrasi: lahirnya KPK yang independen, reformasi birokrasi, hingga beasiswa LPDP. Sayangnya, semangat itu sering berhenti di tengah jalan. Intervensi politik dan patronase membuat banyak kebijakan kehilangan arah jangka panjang.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya meritokrasi. Agenda ini bukan sekadar soal efisiensi, tetapi juga keadilan sosial. Tanpa meritokrasi, generasi muda kehilangan kepercayaan. Dengan meritokrasi, bonus demografi bisa benar-benar menjadi kekuatan penggerak transformasi bangsa.
Kepemimpinan Prabowo membawa pergeseran: dari reformasi menuju transformasi. Koreksi tetap penting, tetapi transformasi lebih utama. Ia menekankan kemandirian pangan, energi, teknologi, dan industrialisasi pertahanan. Semua itu membutuhkan meritokrasi dan tenaga generasi muda.
Prabowo sering berpesan, “Kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Kemandirian bangsa lahir bila kita memperkuat manusia Indonesia.” Pesan ini menegaskan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi juga martabat bangsa.
Menuju Indonesia Emas
Generasi muda harus menjadi subjek, bukan objek politik. Mereka sudah membuktikan diri melalui startup, UMKM digital, olahraga, dan seni. Politik pun harus memberi ruang bagi mereka melalui kaderisasi yang transparan dan meritokratis.
Pengalaman saya di organisasi mahasiswa, profesi, hingga dunia profesional memperlihatkan hal sama: energi anak muda besar, tetapi sering tersumbat sistem tertutup. Transformasi hanya mungkin terjadi jika ruang itu dibuka dengan meritokrasi.
Transformasi Indonesia membutuhkan peta jalan. Fase 2025–2030: menata birokrasi, mempercepat hilirisasi, dan menanamkan future skills. Fase 2030–2040: industrialisasi penuh, digitalisasi menyeluruh, dan kemandirian energi. Fase 2040–2045: Indonesia menjadi negara maju.
Pada 2045, mereka yang kini berusia 20-an akan menjadi pemimpin bangsa. Jika meritokrasi ditegakkan, mereka siap menjadi pemimpin emas. Jika tidak, kita terjebak dalam siklus krisis dan kehilangan momentum sejarah.
Tulisan Bagas tentang jihad institusi adalah alarm penting bahwa bangsa ini butuh pembenahan. Namun, kita tak boleh berhenti pada alarm. Kita harus menulis mimpi yang lebih besar: transformasi Indonesia.
Transformasi berarti menyiapkan bangsa ini melampaui koreksi menuju kemandirian. Transformasi berarti menjadikan bonus demografi sebagai mesin sejarah. Transformasi berarti menegakkan meritokrasi sebagai jalan utama untuk melahirkan kepemimpinan muda.
Indonesia hari ini tidak butuh sekadar reformasi jilid dua. Indonesia butuh transformasi total: membangun institusi meritokratis, menggerakkan generasi muda, dan mewujudkan kemandirian bangsa. Inilah jalan menuju Indonesia Emas 2045.
Jika berhasil, Indonesia akan berdiri tegak bukan hanya karena pertumbuhan ekonomi, tetapi juga karena martabatnya. Transformasi Indonesia adalah jalan meritokrasi, jalan generasi muda, dan jalan kemandirian bangsa. Sebuah mimpi yang harus menjadi kenyataan.